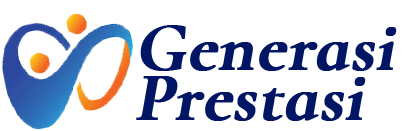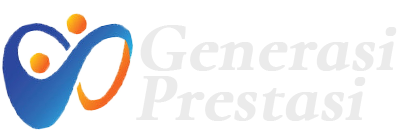Jakarta –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2016 mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk merumuskan Visi Indonesia Emas 2045. Di dalam visi tersebut, termuat gambaran kondisi Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan dan peta jalan untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2045.
Visi Indonesia Emas ini tidak terlepas dari dukungan data kondisi demografi penduduk Indonesia yang periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Ini akan menjadi jendela peluang bagi suatu negara untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai salah satu unit utama (unit eselon I) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pendidikan vokasi telah digadang-gadang oleh Pemerintahan Jokowi diharapkan dapat memainkan peran krusial dalam memanfaatkan bonus demografi dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan siap kerja, pendidikan vokasi dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan demografis dan memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.
Pendidikan vokasi merupakan sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Tujuan utama pendidikan vokasi terletak pada keuntungan ekonomi untuk masa depan.
Pada era presiden Jokowi, pendidikan tinggi vokasi telah menjadi salah satu fokus dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendukung pembangunan ekonomi berbasis keterampilan guna menyongsong visi Indonesia Emas pada tahun 2045, upaya yang telah dilakukan antara lain:
- Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Program ini bertujuan menyelaraskan kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri, melakukan modernisasi fasilitas dan peralatan pendidikan, serta meningkatkan kompetensi dosen vokasi melalui pelatihan dan magang di industri.
- Konsep link and match antara pendidikan dan industri, seperti: kerja sama dengan industri dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, peningkatan program magang industri bagi mahasiswa vokasi, dan mendorong keterlibatan industri dalam sertifikasi kompetensi lulusan.
- Mendorong pembentukan politeknik dan pengembangan sekolah vokasi di perguruan tinggi, termasuk dengan teaching factory-nya.
- Dalam konteks merdeka belajar, mahasiswa vokasi juga diberi kesempatan untuk belajar di luar kampus melalui program magang, pertukaran pelajar, atau proyek-proyek yang berhubungan dengan dunia kerja, dan fleksibilitas dalam menentukan cara belajar yang lebih relevan
Meskipun masih butuh banyak perbaikan dan penyempurnaan, namun realitanya upaya-upaya yang diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas pendidikan tinggi vokasi tersebut telah berjalan dan dimanfaatkan oleh semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.
Selain itu, diterbitkan juga Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PVPV) yang diistilahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menjadi enam pilar:
Pilar pertama, perancangan sistem informasi pasar kerja. Pilar kedua, penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi dan SMK Pusat Keunggulan. Pilar ketiga, penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis link and match dan dual system. Pilar keempat, penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, future job, skilling, reskilling, dan upskilling. Pilar kelima, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan. Pilar keenam, peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Dapat dikatakan, komitmen Presiden Jokowi terhadap pendidikan tinggi vokasi cukup baik. Namun demikian, terdapat beberapa catatan yang setidaknya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan pendidikan tinggi vokasi ke depan, di antaranya:
a. Kualitas pengajar yang belum merata. Tidak sedikit perguruan tinggi vokasi, terutama yang swasta dan atau yang di daerah masih mengalami kekurangan tenaga pengajar yang memiliki pengalaman praktis atau kompetensi yang relevan dengan dunia industri. Sering kali, tidak terlalu menguasai keterampilan praktis yang dibutuhkan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), hal ini karena rata-rata tenaga pengajar yang ada berasal dari perguruan tinggi dengan latar belakang akademis (non vokasi) sehingga rata-rata pendekatan pengajarannya menggunakan pendekatan akademis. Program-program dari Direktorat Jenderal Vokasi dalam meningkatkan kualitas pengajar yang meliputi magang, pelatihan, dan sertifikasi belum sepenuhnya bisa banyak menyasar tenaga pengajar pada perguruan tinggi vokasi.
b. Terbatasnya fasilitas dan infrastruktur. Banyak perguruan tinggi vokasi yang masih memiliki fasilitas dan peralatan praktikum yang tidak memadai, tidak layak, dan kurang sesuai dengan standar industri modern, terlebih untuk keperluan teaching factory. Ini banyak terlihat pada perguruan tinggi vokasi swasta dan atau yang di daerah, sehingga sering kali alumni yang dihasilkan, gagap dan sering dianggap tidak cakap ketika masuk ke DUDI dan memanfaatkan peralatan/fasilitas kerja yang ada, termasuk peralatan teknologi digital yang menjadi ciri revolusi industri 4.0, seperti: internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan otomatisasi.
c. Kurangnya sinkronisasi dengan kebutuhan DUDI. Meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan ‘link and match’ antara dunia pendidikan tinggi dan industri, akan tetapi masih ada kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di institusi pendidikan tinggi vokasi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.
Sebagaimana di negara-negara maju seperti Jerman dan Swiss, pendidikan tinggi vokasi diselenggarakan atas dasar Job Order oleh DUDI, baik nama dan jenjang pendidikannya, kurikulumnya, maupun learning outcome-nya. Link and Match yang saat ini menjadi slogan, belum sepenuhnya diimplementasikan secara sistemik, holistik, dan berkesinambungan, sehingga sering kali lulusan pendidikan tinggi vokasi tidak siap sepenuhnya untuk masuk ke dunia kerja.
d. Dorongan pembentukan Politeknik dan pengembangan Sekolah Vokasi di berbagai perguruan tinggi, serta dorongan perguruan tinggi negeri untuk menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) / BLU (Badan Layanan Umum) yang pada akhirnya PTN terpaksa menerima banyak mahasiswa baru untuk membiayai operasional kampus. Hal ini membuat kesenjangan dan permasalahan tersendiri bagi perguruan tinggi vokasi, terutama yang swasta dan atau yang di daerah. Ini dikarenakan persaingan dalam mendapatkan mahasiswa baru semakin kompetitif, terlebih perguruan tinggi vokasi swasta yang hampir seluruh biaya operasionalnya rata-rata bergantung pada biaya yang dibayarkan oleh mahasiswanya.
e. Stigma terhadap pendidikan tinggi vokasi. Pendidikan tinggi vokasi masih sering dijadikan sebagai pilihan kedua dibandingkan pendidikan akademik. Tidak sedikit orang tua dan siswa yang memandang pendidikan vokasi sebagai pilihan yang kurang prestisius atau kurang bergengsi, sehingga menyebabkan rendahnya minat terhadap pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi vokasi juga sering diklaim sebagai “sekolah tukang” yang hanya mencetak teknisi saja, tanpa jenjang karier yang jelas di DUDI.
f. Instrumen akreditasi dengan pendekatan pendidikan vokasi. Perlunya penyesuaian atau pembeda penilaian penjaminan mutu melalui BAN-PT pada instrumen akreditasi khusus untuk Pendidikan Tinggi Vokasi, sehingga pendekatannya tidak menggunakan pendekatan akademik akan tetapi menggunakan pendekatan vokasional.
Terhadap evaluasi ini, pemerintah masih sangat perlu melakukan intervensi dalam pengembangan pendidikan tinggi vokasi melalui kebijakan-kebijakan yang diproduksi dan berbagai hibah/bantuan untuk pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Dengan begitu, pendidikan vokasi dapat semakin bermutu dan berkualitasguna menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.
Pemerintah juga perlu memanfaatkan bonus demografi yang ada, dengan tanpa mendikotomikan perguruan tinggi vokasi negeri atau swasta, di kota besar maupun di daerah. Kampanye besar-besaran mengenai pendidikan tinggi vokasi juga sangat diperlukan, seperti kampanye SMK Bisa, SMK Hebat, agar stigma masyarakat terhadap pendidikan tinggi vokasi semakin baik.
Semua pihak juga perlu berkomitmen lebih kuat, termasuk penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, sektor swasta, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam mendukung perkembangan pendidikan tinggi vokasi yang lebih baik lagi.
Ginanjar Wiro Sasmito
Direktur Eksekutif Perkumpulan Politeknik Swasta (Pelita) Indonesia / Wakil Direktur IV Politeknik Harapan Bersama
(Content Promotion/Politeknik Harapan Bersama)